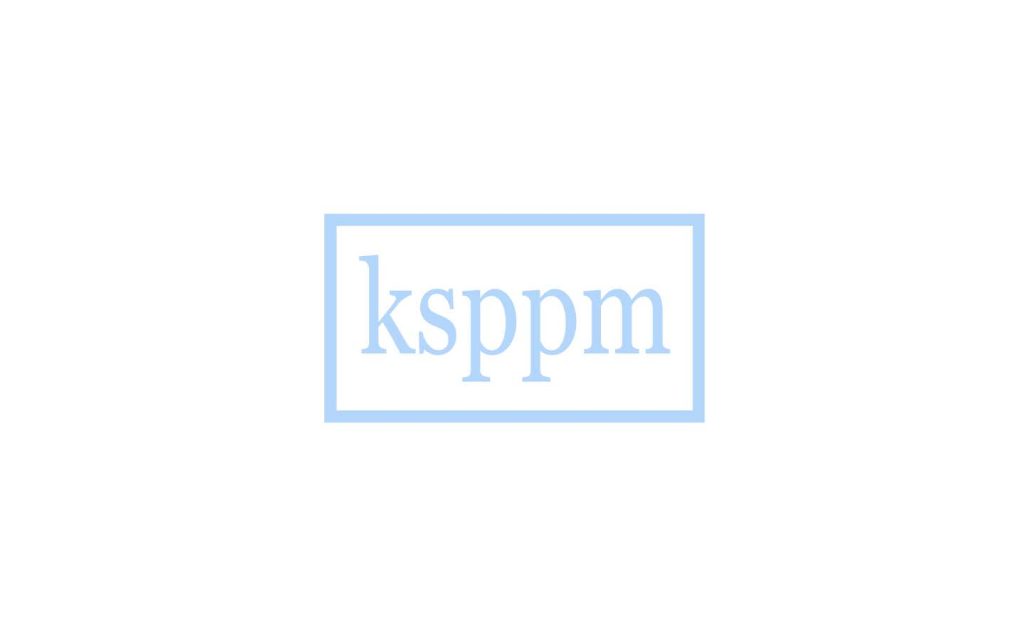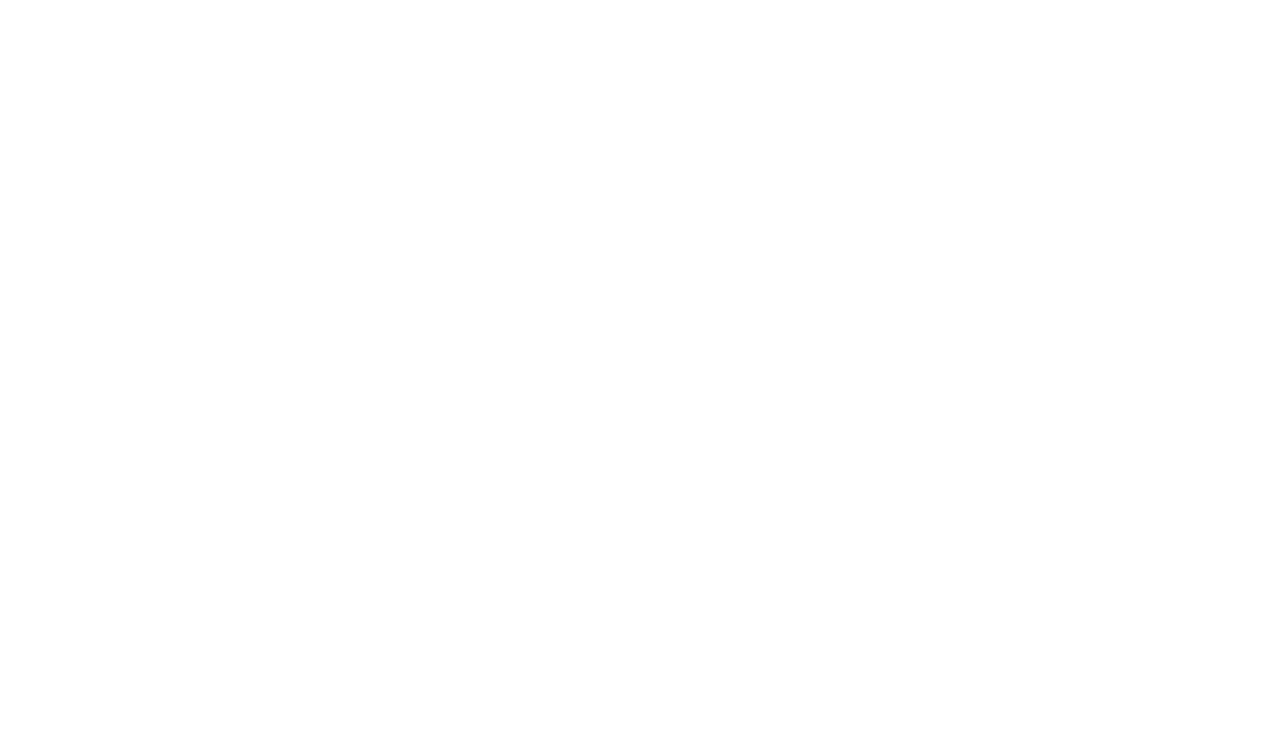Sejak awal kehadirannya di Bona Pasogit, keberadaan PT Inti Indorayon Utama (IIU) – yang kemudian bertransformasi menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL) – tidak pernah lepas dari penolakan. Sejarah Gerakan penolakan terhadap Perusahaan ini bisa dibaca sebagai sebuah jejak panjang perjuangan rakyat untuk melawan kerusakan sosio-ekologis yang diakibatkan oleh beroperasinya Perusahaan ini.
Gerakan ini bukan bersifat reaktif sesaat, melainkan bersambung lintas generasi, dengan dinamika dan bentuk perlawanan yang terus berkembang. Setiap babak penolakan mencermintan perubahan konteks politik-ekonomi nasional dan local, tetapi tetap berakar pada satu hal yang sama: penolakan terhadap model pembangunan ekstraktif yang mengabaikan hak dan suara rakyat dan keberlanjutan ekologis.
4.1 Penolakan Pembangunan Pabrik di Sosor Ladang (1986 – 1992)
Sejak perdebatan mengenai izin lokasi pabrik Indorayon mencuat di tingkat internal birokrasi dan diliput secara luas oleh media massa pada awal tahun 1985, perhatian publik pun mulai tumbuh. Pemberitaan tersebut memicu kekhawatiran di kalangan warga Porsea dan organisasi non-pemerintah (ornop) setempat, yang kemudian mulai memperbincangkan potensi dampak negatif dari kehadiran pabrik Indorayon.
Kekecewaan dan ketidakpuasan warga terhadap Indorayon mulai muncul dalam proses pembebasan tanah yang kelak dijadikan lokasi pabrik. Lokasi pabrik seluas 225 hektar yang berada di Silosung, Sosorladang, Porsea, sebelumnya merupakan areal penggembalaan ternak, sebagian areal persawahan, dan juga ditemukan kolam ikan yang ditumbuhi tanaman bayon yang secara tradisional dipergunakan penduduk untuk menganyam tikar. Dalam proses pembebasan tanah yang dimaksud, beberapa warga desa sempat melakukan protes. Pasalnya, Ganti rugi yang diterima dinilai kurang layak dan merata, serta proses pelepasan tanah yang tidak menghormati budaya masyarakat batak. Proses pelepasan tanah tersebut juga dilakukan secara sepihak.[1]
Gerakan perlawanan yang terjadi di era ini masih belum terorganisir dengan baik dan sifatnya masih sangat kasuistik. Tuntutan rakyat meliputi ganti rugi atas pelepasan tanah dan menuntut tanah untuk dikembalikan. Tuntutan-tuntutan ini juga merupakan respon langsung dari masyarakat yang merasa keberatan dengan praktik pencaplokan tanah dan proses manipulasi adat yang dilakukan oleh PT IIU.
“… Sejak 1983 PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) mengambil tanah rakyat dengan cara tipu muslihat, seperti saat PT IIU membeli tanah rakyat dengan “pago-pago”, satu cara adat yang disalahgunakan. Karena adat pago-pago bukanlah adat jual beli tanah. Tetapi pago-pago adalah sejenis adat Batak Toba yang dianggap mensyahkan satu transaksi atau periswa dengan memberikan upah saksi yang dinamakan “upa raja”. “…dalam hal ini, PT IIU telah menipu rakyat dan disetujui, bahkan, dikukuhkan pula oleh pemerintah dalam hal ini gubernur dan bupati.[2] Pada 1990, setelah mendapatkan izin Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), mereka mulai menggantikan pohon-pohon alam dengan tanaman monokultur, seperti eukaliptus.
4.2 Gerakan Menutup Indorayon (1993 -1997)
Pada tahun 1993, perlawanan terhadap PT IIU (Indorayon) memasuki babak krusial. Gerakan yang sebelumnya bersifat lokal dan kasuistik, mulai menampakkan bentuknya sebagai gerakan kolektif. Pemicunya adalah ledakan boiler dan kebocoran gas klorin pada 5 November 1993, yang menyebabkan tumpahan bahan kimia berbahaya hingga menusuk ke pemukiman warga sekitar.
Peristiwa ini membawa trauma ekologis. Pencemaran udara menyebar hingga radius 40 km, sungai Asahan dipenuhi lumpur limbah yang membunuh ikan dan menyebabkan iritasi kulit pada ibu dan balita. Pengendalian pencemaran udara dan air yang buruk oleh perusahaan menyebabkan penyakit pernapasan dan kulit di kalangan warga lokal. Ikan dan ternak keracunan, dan produktivitas hasil pertanian menurun. Sengketa lahan pun terjadi, karena sebagian besar area konsesi Indorayon dianggap sebagai hutan adat milik masyarakat.[3]
Aksi kolektif pun muncul: ribuan penduduk turun ke jalan, menghalangi akses truk perusahaan, merusak instalasi dan properti perusahaan. Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi puas dengan kompensasi semata; mereka menginginkan penghentian operasional permanen.
Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kemudian mengeluarkan rekomendasi penutupan sementara PT IIU pada 20 November 1993; tak lama kemudian, Pemerintah Pusat memerintahkan audit lingkungan menyeluruh, menugaskan firma auditor Amerika, Labat Anderson Incorporated, untuk menilai dampak ekologis dan kesehatan masyarakat.[4]
Audit ini menjadi bukti bahwa Gerakan rakyat telah memaksa pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan rakyat untuk mengaudit total PT IIU . Kejadian ini memperlihatkan transformasi tajam: dari tuntutan kasuistik menjadi aksi nyata yang berhasil menekan regulasi dan audit lingkungan, sehingga babak ini merupakan kemenangan politik dalam sejarah perlawanan lokal.
Pada tahun 1999, Yayasan Perhimpunan Pencinta Danau Toba (YPPDT) menyerahkan laporan ke Habibie berjudul Dampak Operasi PT Inti Indorayon Utama Terhadap Lingkungan Danau Toba, yang kemudian diterbitkan menjadi buku pada tahun 1999. Laporan ini merupakan respons dari diterbitkannya laporan audit Labat Anderson dan FKM-UI. Karena desakan Gerakan rakyat yang semakin massif di Sumatera Utara dan Upaya YPPDT di Jakarta – walaupun kedua entitas ini tidak memiliki hubungan dalam aktivitasnya, lahirlah keputusan Presiden BJ Habibie : operasi IIU berhenti sementara, sejak 19 Maret 1999. Pabrik IIU praktis berhenti selama kurang-lebih 4 tahun lamanya, sebelum direoperasikan kembali di bawah nama PT Toba Pulp Lestari.[5]
4.3 Gerakan Menolak Reoperasi (1999 – 2005)
Setelah terpilihnya Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 1999, masyarakat Porsea sekitarnya menyambut baik hal ini karena mereka berdua dinilai sebagai pemimpin yang dekat dan berpihak pada rakyat yang kecil. Namun, harapan ini seketika sirna setelah pengumuman sidang cabinet yang dipimpin oleh Wapres Megawati, 10 Mei 2000. Sidang ini tidak dihadiri oleh Gus Dur karena sedang berada di Thailand. Sidang memutuskan untuk menghentikan kegiatan usaha rayon, namun tetap melanjutkan usaha bubur kertas (pulp), tanpa audit. Pemerintah menganggap keputusan ini sebagai jalan keluar yang menguntungkan (win-win solution) bagi masyarakat dan Indorayon. Keputusan ini juga merupakan pilihan terakhir dari 6 alternatif keputusan yang ditawarkan Meneg LH kepada sidang cabinet, di mana diakui hampir semua pilihan memiliki problem dan aspek negative yang menabrak berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. [6]
Keputusan ini jelas memicu kembali reaksi perlawanan masyarakat untuk kembali melakukan aksi demonstrasi ke jalan. Rakyat juga melakukan blockade dan penghadapan terhadap truk-truk yang melintasi daerah mereka, mendirikan posko-posko penjagaan di desa-desa, dan penggalangan massa. Mereka juga menggelar spanduk-spanduk yang intinya menolak reoperasi Indorayon.[7]
Gerakan perlawanan ini tentu menimbulkan terjadinya kekerasan demi kekerasan baik secara vertical dan horizontal. Sementara itu sejumlah Ornop melakukan protes kepada pemerintah untuk meninjau kembali keputusan reoperasi Indorayon. Sebab, jika tidak, maka akan ada potensi terjadinya kekerasan yang lebih brutal dan juga potensi yang menyebabkan terjadinya korban jiwa. Pemerintah juga dituntut agar tidak hanya mementingkan kaum pemodal, yang selama belasan tahun terbukti melakukan ;pelanggaran dan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, solusi terbaik menurut sejumlah Ornop adalah ditutupnya Indorayon secara permanen. [8]
Dengan dinamika yang terjadi di tubuh gerakan sosial dan politik nasional, pada akhirnya PT Indorayon beroperasi kembali dengan nama baru yaitu PT Toba Pulp Lestari dengan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial yang lebih besar. Komitmen PT TPL tertuang dalam Akta Pernyataan Pelaksanaan Komitmen Paradigma PT Toba Pulp Lestari, Tbk Nomor 54.
4.5 Gerakan Sosial Pasca-Paradigma Baru
Setelah bertahun-tahun diwarnai konflik sosial dan lingkungan yang akut di bawah nama PT Inti Indorayon Utama (IIU), perusahaan bubur kertas dan rayon di Sumatera Utara ini berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL) pada tahun 2003. Perubahan nama ini diiringi dengan janji “paradigma baru”: sebuah komitmen untuk menjalankan operasional yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Namun, paradigma baru ini justru menjadi babak baru bagi gerakan sosial yang menolak kehadiran PT TPL.
Dalam beberapa tahun terakhir, eskalasi gerakan sosial mencapai puncaknya. Kegagalan dialog, proses hukum yang berlarut-larut, dan konflik yang terus berulang di lapangan telah mengkristalkan sebuah kesimpulan di kalangan masyarakat dan aktivis: PT TPL dianggap tidak dapat direformasi. Sejak awal janji “paradigma baru” dinilai sebagai ilusi yang tidak mungkin tercapai selama relasi penguasaan sumber daya alam antara masyarakat dan korporasi masih timpang. Sehingga kelompok Gerakan sosial meyakini bahwa satu-satunya solusi untuk melindungi tanah adat, lingkungan hidup, dan masa depan kawasan Danau Toba adalah dengan menghentikan operasional perusahaan secara permanen.
Gerakan “Tutup TPL” menjadi pekik perjuangan bersama yang menyatukan berbagai elemen masyarakat. Tuntutan ini tidak lagi hanya disuarakan oleh komunitas yang berkonflik langsung, tetapi telah menjadi gerakan kolektif yang lebih luas, dimotori oleh aliansi mahasiswa, pemuda, seniman, akademisi, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal maupun nasional.
Tuntutan untuk menutup TPL diperkuat dengan argumen bahwa keberadaan industri pulp skala besar tidak sejalan dengan status Danau Toba sebagai UNESCO Global Geopark, yang seharusnya memprioritaskan pariwisata berkelanjutan, konservasi, dan ekonomi berbasis kearifan lokal. Gerakan ini secara fundamental menantang model pembangunan yang selama ini dianut, dengan menawarkan visi alternatif untuk Tano Batak yang berpusat pada kedaulatan rakyat dan kelestarian ekologis.
Narasi gerakan sosial pasca-paradigma baru PT TPL adalah cerita tentang evolusi perlawanan. Dimulai dari tuntutan pengakuan hak dan perbaikan praktik, kini gerakan tersebut telah sampai pada sebuah tuntutan final: “Tutup TPL”. Ini adalah bukti bahwa perubahan nama dan citra tidak menyelesaikan akar masalah, yaitu benturan fundamental antara model ekonomi ekstraktif dengan hak-hak konstitusional masyarakat adat dan keadilan ekologis. Perjuangan ini menjadi penanda bahwa janji “paradigma baru” harus dibuktikan dengan tindakan nyata, dan ketika janji itu dianggap gagal, masyarakat akan menuntut solusi yang paling radikal sekalipun demi melindungi ruang hidup dan masa depan generasi mereka.
4.5.1 Peran Gereja Dalam Perlawanan PT IIU – PT TPL
Di tengah meningkatnya pengorganisasian komunitas, kelompok-kelompok gereja lokal secara terbuka memperjelas sikap mereka dengan mendukung penuh masyarakat dalam perjuangan mereka melawan Indorayon[9]. Keterlibatan institusi keagamaan ini menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat basis sosial gerakan perlawanan di tingkat akar rumput, yang tumbuh subur seiring melemahnya tekanan dari aparat keamanan.
Dalam mengurai kompleksitas gerakan perlawanan masyarakat Toba terhadap PT Inti Indorayon Utama (IIU), Abdul Wahib Situmorang menempatkan institusi keagamaan sebagai salah satu aktor kunci. Menurutnya, “pemimpin-pemimpin agama, baik sebagai individu maupun institusi, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan legitimasi kepada masyarakat Batak Toba yang berjuang untuk menutup IIU.”[10] Peran ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui sebuah proses panjang yang penuh dengan tantangan internal dan tekanan eksternal.
Keterlibatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sebagai gereja mayoritas di Tano Batak dimulai secara signifikan pada tahun 1989. Momen ini ditandai oleh sikap Pucuk Pimpinan HKBP yang baru, Dr. S.A.E Nababan, yang “mengkritik IIU karena bertanggung jawab atas begitu banyak masalah, seperti tanah longsor di desa Sianipar dan konflik tanah di Sugapa.”[11] Sikap kritis Nababan menjadi pemantik, yang kemudian membuka ruang bagi pendeta-pendeta lain untuk menyuarakan hal yang sama, meskipun pada awalnya gereja “tidak siap untuk berkonfrontasi dengan pemerintah karena individu-individu merasa terancam secara fisik dan psikologis oleh militer dan polisi.”[12]
Namun hampir satu decade pasca paradigma baru, suara gereja tidak lagi terdengar untuk membela kaum miskin dan tertindas. Bahkan, banyak gereja yang bekerja sama dan menerima bantuan dari PT TPL untuk beberapa program termasuk pembangunan gereja.
Memasuki tahun 2025, peran gereja di kawasan Danau Toba dalam menyikapi keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) muncul kembali akibat semakin seringnya terjadi bencana ekologis dan kekerasan yang terjadi di wilayah-wilayah yang sedang diperjuangkan oleh komunitas Masyarakat Adat.
Pada pertengahan tahun 2025, pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Ephorus Pdt. Dr. Victor Tinambunan, secara terbuka menyerukan agar pemerintah menutup permanen operasi PT TPL.[13] Seruan ini didasarkan pada pengamatan selama puluhan tahun yang menunjukkan bahwa kehadiran TPL telah memicu krisis ekologi, seperti banjir bandang, dan konflik sosial yang berkepanjangan.[14] Ephorus menegaskan bahwa HKBP memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan lingkungan melalui pendekatan agama dan tidak menginginkan konflik terus terjadi antara masyarakat dengan perusahaan.[15]
Dukungan serupa juga datang dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), yang secara tegas menyatakan bahwa gereja harus berdiri di garda terdepan dalam advokasi terhadap masyarakat adat dan lingkungan hidup mereka.[16] PGI bahkan menegaskan bahwa kehadiran perusahaan lebih banyak meninggalkan luka daripada kesejahteraan.[17]
Perlawanan gereja kini tidak hanya didasari oleh dampak sosial, tetapi juga oleh landasan teologis yang kuat. PGI dan para pimpinan gereja di Sumatera Utara secara aktif menggaungkan seruan “pertobatan ekologis”.[18] Mereka menekankan bahwa merawat bumi dan alam semesta adalah perintah Tuhan, dan tanah bukanlah sekadar komoditas atau aset yang bisa dieksploitasi, melainkan warisan leluhur yang harus dihormati.[19] Pemahaman inilah yang menjadi sumber spiritual bagi gereja untuk terus menyuarakan perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan ekologis.
Salah satu transformasi paling signifikan dari peran gereja saat ini adalah aliansi yang semakin erat dengan gerakan Masyarakat Adat. Perjuangan tidak lagi terpisah; gereja secara aktif mendukung perjuangan komunitas adat dalam mempertahankan tanah ulayat mereka yang masuk ke dalam konsesi PT TPL.[20] Gereja-gereja seperti HKBP dan HKI secara terbuka merespons dan mengecam tindakan kekerasan atau kriminalisasi yang menimpa para pejuang adat, seperti kasus yang menimpa Sorbatua Siallagan.[21] Keberpihakan ini menegaskan bahwa bagi gereja, perjuangan ini adalah isu hak asasi manusia yang fundamental.
Meskipun demikian, peran aktif gereja juga menghadapi tantangan, termasuk dari dalam. Sejumlah jemaat yang merupakan pekerja TPL menyatakan kekecewaan atas seruan penutupan dari Ephorus HKBP, menunjukkan adanya dilema antara kelestarian lingkungan dan kebutuhan ekonomi.[22] Di sisi lain, perusahaan juga aktif mendekati komunitas gereja melalui program bantuan sosial dan renovasi rumah ibadah, sebuah strategi untuk membangun hubungan baik di tingkat akar rumput.[23]
[1] Dimpos Manalu “Gerakan Sosial dan Kebijakan Publik (studi terhadap peran gerakan perlawanan masyarakat dalam mengubah kebijakan pemerintah mengenai PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea Sumatera Utara)”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, Tesis, Hal.160
[2] Bungaran Antonius Simanjuntak, Belajar Dari Rakyat, Perjalanan KSPPM Mendorong Perubahan Sosial di Tapanuli, KSPPM, 2013, Hal. 51
[3] Ko Nomura, Democratization and The Politics of Environmental Claim – Making : A Story From Indonesia, South East Asia Research, 2009, Hal.269
[4] Lihat Laporan Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL Yang Diserahkan Ke Presiden Jokowi, Indorayon – Toba Pulp Lestari (TPL) Sumber Bencana Bagi Masyarakat Kitaran Kaldera Toba, 2021
[5] Dimpos Manalu, Studi Tentang Indorayon : Pertarungan Intelektual – Organik vs Intelektual – Tukang, Belajar Dari Rakyat, Perjalanan KSPPM Mendorong Perubahan Sosial di Tapanuli, KSPPM, 2013, Hal.219
[6] Dimpos Manalu “Gerakan Sosial dan Kebijakan Publik (studi terhadap peran gerakan perlawanan masyarakat dalam mengubah kebijakan pemerintah mengenai PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea Sumatera Utara)”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, Tesis, Hal.261
[7] Effendi Panjaitan, “Tapasadama Rohanta Menutup Indorayon: Kisah Perjuangan Rakyat Toba Samosir Melawan PT Inti Indorayon Utama”, dikutip dalam Dimpos Manalu, Gerakan Sosial dan Kebijakan Publik (studi terhadap peran gerakan perlawanan masyarakat dalam mengubah kebijakan pemerintah mengenai PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea Sumatera Utara)”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, Tesis, Hlm.263
[8] Lihat “LSM Tuntut Pemerintah Tinjau Ulang Operasional IIU”, Harian Kompas, 26 Juni 2000
[9] Ko Nomura, “Democratization and the Politics of Environmental Claim-Making: A Story from Indonesia,” South East Asia Research 17, no. 2 (2009): 274.
[10] Abdul Wahib Situmorang, “Contentious Politics in Toba Samosir: The Toba Batak Movement Opposing the PT. Inti Indorayon Utama Pulp and Rayon Mill in Sosor Ladang-Indonesia (1988 to 2003)” (MA Thesis, Ohio University, 2003) hlm. 154.
[11] Ibid., hlm. 154.
[12] Ibid., hlm. 155.
[13] “Seruan Ephorus HKBP untuk Menutup TPL”, Mongabay Indonesia, 17 Mei 2025; dan “HKBP Serukan Pemerintah Tutup TPL”, Suara HKBP, 15 Mei 2025.
[14] “Otoritas Gereja Batak Serukan Penutupan PT TPL”, Mongabay Indonesia, 17 Mei 2025.
[15] “HKBP Serukan Pemerintah Tutup TPL”, Suara HKBP, 15 Mei 2025; dan “Otoritas Gereja Batak Serukan Penutupan PT TPL”, Mongabay Indonesia, 17 Mei 2025.
[16] “Gereja di Garda Terdepan Advokasi Masyarakat Adat dan Lingkungan”, pgi.or.id, 18 Juni 2025.
[17] “PGI Ultimatum TPL Hengkang dari Tanah Batak”, SINDOnews.com, 20 Februari 2025.
[18] “Semiloka Teologi dan Penjemaatan DKG Wilayah Sumut Serukan Pertobatan Ekologis”, pgi.or.id, 22 Maret 2025.
[19] “Gereja dan Lingkungan Hidup: Merawat Bumi sebagai Ciptaan Tuhan”, Jurnal Teologi Kontekstual, Vol. 5, No. 1, 2024.
[20] “Aliansi Masyarakat Adat dan Gereja Tolak Operasi TPL”, aman.or.id, 15 Juni 2025.
[21] “HKI Kecam Tindakan Kekerasan Terhadap Pejuang Lingkungan”, hki.org, 25 Januari 2024; dan “PGI Minta Negara Hadir Lindungi Masyarakat Adat”, pgi.or.id, 12 Februari 2025.
[22] “Serikat Pekerja TPL dan Mitra Kecewa Pernyataan Ephorus: Kami Jemaat HKBP Bergantung Hidup sama TPL”, Tribun-medan.com, 7 Mei 2025.
[23] “TPL Kembali Serahkan Bantuan di HKBP Marom”, PT Toba Pulp Lestari Tbk., 23 Februari 2019.