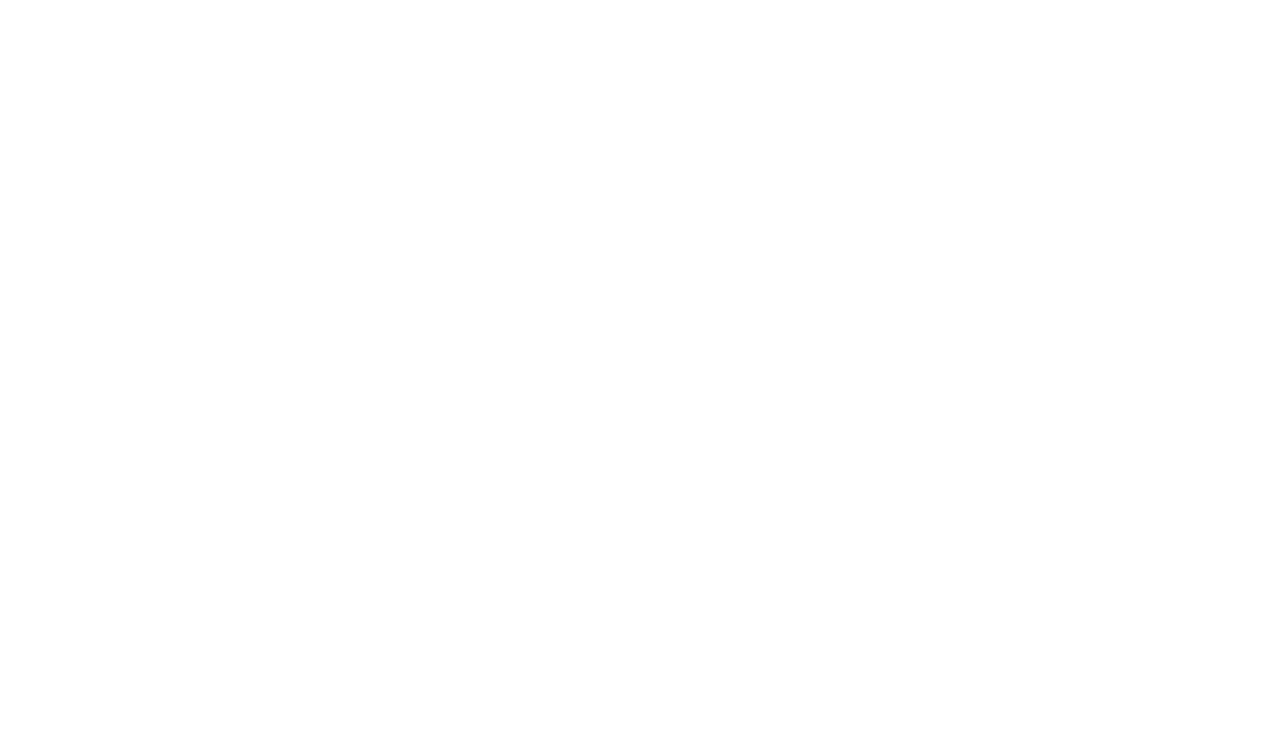Pada Selasa, 4 Oktober 2022. perjuangan masyarakat adat kembali dibicarakan di ruang akademik. Kali ini, KSPPM bekerjasama dengan Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik Universitas Sumatera Utara (IAP USU) menyelenggarakan diskusi buku “Nunga Leleng Hami Mian di Son” bertempat di Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) USU
Kalang Zakaria dari KSPPM sebagai salah satu penulis buku memaparkan proses verifikasi dan identifikasi masyarakat adat pada 2021 lalu di Kabupaten Toba dan Taput. Peristiwa yang dia saksikan secara langsung itulah yang dia tuliskan di dalam buku. Ia melihat bagaimana Tim Verifikasi terkesan tidak percaya kepada masyarakat adat. Ia juga menjelaskan asal-usul konflik masyarakat adat dengan negara, yaitu tumpang-tindih klaim. Masyarakat adat memiliki tata-ruang yang lengkap di wilayah adatnya (harangan (hutan), parhutaan (pemukiman), parhaumaan (persawahan), parjampalan (tempat menggembala ternak), dll. Namun secara tiba-tiba negara menunjuk dan menetapkan wilayah adat menjadi kawasan hutan negara (hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, dll.
Selain itu, negara memiliki perspektif berbeda mengenai masyarakat adat. Seperti yang kita ketahui, terdapat tiga sifat penguasaan wilayah adat: (a) publik-privat, (b) tanah komunal, dan (c) tanah adat perorangan. Sementara itu, pemahaman Negara mengenai penguasaan wilayah adat hanya bersifat komunal. Pemahaman negara mengenai masyarakat adat cenderung kaku. Padahal masyarakat adat juga berdinamika sesuai perkembangan zaman.


Yando Zakaria, juga salah satu penulis buku, melontarkan kritik kepada pemerintah yang terkesan lambat dalam penyelesaian konflik agraria. Sebagai ahli tentang desa dan masyarakat adat, Yando berpendapat bahwa verifikasi mestinya tidak perlu untuk memperoleh pengakuan terhadap masyarakat adat. “Hanya perlu bertanya siapa marga raja dalam sebuah huta (kampung); akan jelas siapa pemilik wilayah adat tersebut. Bagi orang Batak, marga adalah tanah dan tanah adalah marga,” katanya tegas. Menurut Yando, problem akut dalam proses pengakuan masyarakat adat dan hutan adat adalah kriteria dan indikator yang berorientasi masa lalu, yaitu bahwa masyarakat adat selalu dianggap sebagai kumpulan orang kolot yang tidak pernah beradaptasi. Tim verifikasi teknis sangat hegemonik dan tata-cara yang dilakukan dalam proses ini sangat politis.
“Setiap tahun, KLHK hanya bisa memverifikasi 15 komunitas masyarakat adat. Kalau dengan kemampuan negara seperti saat ini, maka konflik wilayah adat baru akan selesai 660 tahun kemudian.” ucapnya.
Dalam diskusi tersebut, Sandra Moniaga dari Komnas HAM memaparkan bagaimana pemerintah melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat. Terjadi kriminalisasi, penangkapan, pelanggaran hak untuk hidup nyaman, hilangnya jaminan hak atas pengetahuan tradisional. Perampasan tanah yang dialami masyarakat adat terjadi dengan sangat sistematis dan terus-menerus.
Dr. Zulkifli Lubis, dosen Antropologi USU, mengatakan bahwa seluruh masyarakat adat di Indonesia menghadapi persoalan yang sama karena menghadapi tembok yang sama yaitu pemerintah lewat proses verifikasi dan identifikasi yang berbelit-belit. Dalam pandangan pemerintah, masyarakat adat itu antara ada dan tiada. Disebut ada karena tertulis dalam regulasi, tetapi nyatanya tiada karena implementasi regulasinya gagal.
“Ada empat kekuatan yang bisa menyingkirkan masyarakat adat dari wilayah adatnya, yaitu regulasi, kekuasaan (power), pasar (market), dan legitimasi. Langkah yang perlu dilakukan adalah tetap mengawal dan mempengaruhi regulasi, menguatkan narasi legitimasi mengenai masyarakat adat,” sarannya.

Seorang mahasiswa IAP USU yang hadir menanyakan apa persisnya yang menyulitkan masyarakat adat dalam proses verifikasi. Lewat sesi diskusi, dia memahami betapa Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 benar-benar tidak berpihak kepada masyarakat adat. Regulasi tersebut telah memaksa masyarakat adat untuk tidak menjadi dirinya sendiri melainkan menjadi masyarakat adat versi negara. Dosen IAP USU, Dr. Asimayanti, juga melihat bagaimana tim verifikasi telah memaksakan konsep dan indikator kepemilikan wilayah adat sehingga menurutnya tim verifikasi perlu melakukan pemaknaan terhadap masyarakat adat agar tidak terjadi bias terhadap masyarakat adat. Beliau berharap agar mahasiswa IAP melek terhadap isu masyarakat adat dan pemerintahan desa yang berbasis adat agar kebijakan-kebijakan yang lahir di masa depan berpihak kepada masyarakat adat.**